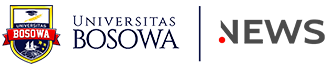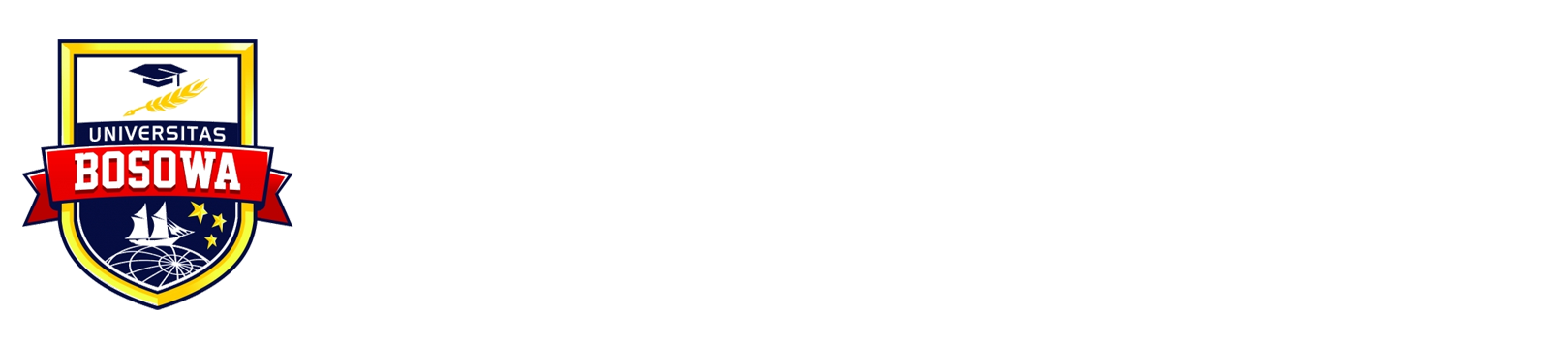Dalam beberapa tahun terakhir, wajah otonomi daerah di Indonesia menghadapi tantangan serius yang memerlukan refleksi mendalam. Penurunan tajam transfer keuangan dari pusat ke daerah dalam APBN 2026 menjadi salah satu isu krusial. Pemerintah hanya mengalokasikan Rp650 triliun untuk daerah, turun hampir 29% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp919 triliun. Kondisi ini kontras dengan meningkatnya belanja pemerintah pusat sebesar 17,8%, dari Rp2.663,4 triliun menjadi Rp3.136,5 triliun. Ketimpangan ini membuat pemerintah daerah harus mencari sumber pembiayaan alternatif, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketergantungan fiskal daerah pada dana transfer pusat yang terlalu tinggi menegaskan fenomena flypaper effect. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, pada 2025 rata-rata PAD daerah hanya berkontribusi sekitar 37,5% dari total pendapatan daerah. Hanya 14 provinsi yang mampu mencatat PAD di atas rata-rata, sementara 20 provinsi lainnya masih bergantung lebih dari 60% pada dana pusat. Beberapa kabupaten bahkan memiliki ketergantungan hingga 800% terhadap dana perimbangan, seperti Kabupaten Bangli di Bali. Kondisi ini menunjukkan bahwa transfer dana justru membuat sebagian daerah kurang terdorong menggali potensi PAD secara mandiri.
Keterbatasan fiskal telah mendorong sejumlah daerah mengambil langkah instan dengan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Bone, dan Jombang, dengan kenaikan hingga 250–1000%. Kebijakan ini sering kali berorientasi pada target jangka pendek untuk menutup kekurangan anggaran pembangunan, namun di sisi lain memicu protes masyarakat, menurunkan daya beli, hingga menghambat pertumbuhan usaha kecil. Jika terus berlanjut, kebijakan semacam ini berpotensi memperburuk kualitas layanan publik dan memperlambat pembangunan daerah.
Selain tantangan fiskal, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tumpang tindih kewenangan, perubahan regulasi yang berulang, dan keterbatasan kapasitas birokrasi. Situasi ini membuat kebijakan di tingkat daerah sering bersifat reaktif dan pragmatis. Banyak kepala daerah lebih memilih kebijakan “mudah”, seperti menaikkan pajak, ketimbang mengembangkan sumber pendapatan inovatif, mengoptimalkan aset, atau membangun kolaborasi lintas sektor.
Pemangkasan dana transfer seharusnya tidak menjadi beban tambahan bagi rakyat. Seperti yang pernah disampaikan Profesor Ryaas Rasyid, situasi ini justru harus menjadi momentum bagi daerah untuk berinovasi. Pemerintah pusat perlu memberikan ruang dan kepercayaan lebih besar kepada pemerintah daerah, sekaligus memastikan adanya supervisi dan pengawasan yang konsisten agar pengelolaan fiskal berjalan transparan dan akuntabel.
Pemerintah daerah perlu membangun kapasitas birokrasi yang adaptif, terbuka terhadap data, dan berbasis partisipasi publik. Pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan serta insentif untuk pelayanan publik berkualitas merupakan langkah penting menuju kemandirian fiskal. Otonomi daerah yang sehat harus mampu mengubah pemerintah daerah menjadi motor penggerak pembangunan, bukan sekadar pengelola dana transfer.
Spirit desentralisasi dan otonomi daerah yang lahir dari semangat Reformasi 1998 menuntut komitmen untuk memperkuat kreativitas dan pemberdayaan lokal. Penurunan dana transfer dari pusat harus dibarengi dengan reformasi birokrasi pusat yang lebih ramping dan profesional. Tanpa langkah nyata tersebut, inovasi akan sulit tumbuh, dan kebijakan jangka pendek yang merugikan masyarakat akan terus berulang.
Ke depan, arah desentralisasi harus menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan dengan dukungan kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat. Kolaborasi, inovasi, dan akuntabilitas menjadi kunci menciptakan pemerintahan daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.